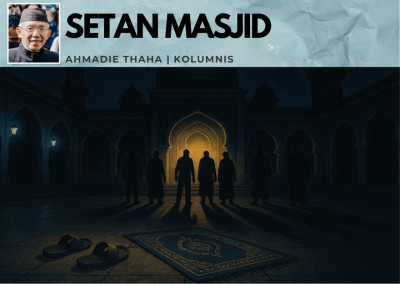REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Mubasyier Fatah (Bendahara Umum PP ISNU, Pengamat Pesantren)
Pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan tertua di Nusantara. Bahkan, Pondok Pesantren Al-Kahfi yang terletak di Desa Sumberadi, Kebumen Jawa Tengah tercatat berdiri pada tahun 1475, menjadikannya salah satu pesantren tertua di Asia Tenggara.
Dari pesantrenlah lahir tokoh-tokoh bangsa yang tidak hanya alim dalam ilmu agama, tetapi juga tangguh dalam memperjuangkan kemerdekaan, mengabdi di tengah masyarakat, dan menebar kasih sayang melalui ilmu dan keteladanan.
Namun, dalam dekade terakhir, wajah pesantren mengalami perubahan yang signifikan. Modernisasi membawa pesantren memasuki fase baru: berinovasi, berkembang secara ekonomi, bahkan ikut bersaing dalam dunia bisnis.
Tentu saja, gerakan modernisasi pesantren tidak menjadi masalah, selama tidak menghilangkan orientasi utamanya: menebar cahaya ilahi dan membina generasi yang hidup dengan cita-cita luhur.
Sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya. Semakin banyak pesantren tergelincir dalam arus komersialisasi. Mereka mulai lebih fokus pada pengembangan unit bisnis, memperluas aset-aset properti, memungut biaya pendidikan selangit, membangun citra keagamaan sebagai daya jual, dan melupakan misi utama sebagai tempat pembentukan karakter dan spiritualitas. Akibatnya, pesantren bukan lagi menjadi tempat riyadhah (latihan jiwa), tapi malah menyerupai korporasi berbaju agama.
Krisis Identitas Pesantren
Memang, pada masa lalu, para kiai yang tampil sebagai pendiri dan pengelola pesantren hidup dalam kesederhanaan, tetapi memancarkan kewibawaan. Mereka disegani dan dihormati bukan karena kekayaan atau fasilitas mewah, melainkan karena keilmuannya, keikhlasannya, dan pengaruh moralnya.
Santri datang dari berbagai pelosok dengan niat belajar, mengabdi, dan menempa diri menjadi manusia yang berguna. Tidak ada biaya mahal, tidak ada branding di media sosial, dan tidak ada glorifikasi.
Namun kini, kita menyaksikan pemandangan berbeda. Beberapa pesantren elite bahkan memiliki daftar tunggu masuk yang panjang, biaya pendaftaran puluhan juta, seragam yang distandarkan layaknya sekolah internasional, hingga pembangunan hotel, mal mini, dan rumah makan di dalam kompleks pesantren. Para santri dilatih bukan hanya menjadi ulama, tapi juga entrepreneur, seleb media sosial, atau “influencer syariah”.
Tentu tidak ada yang salah dengan modernisasi. Pesantren memang harus beradaptasi agar tetap relevan. Akan tetapi, ketika orientasi utamanya bukan lagi menyucikan jiwa dan mencerdaskan akal, melainkan menggandakan aset dan menaikkan pamor, maka yang terjadi adalah krisis identitas. Pesantren kehilangan ruh-nya, menjadi nama tanpa jiwa, label tanpa isi.
Fakta dan Data: Kemerosotan Ruhiah Pesantren
Hasil sebuah survei yang dilakukan oleh Pusat Studi Pendidikan Islam Progresif pada 2023 terhadap 300 pesantren di Jawa dan luar Jawa menunjukkan bahwa hanya sekitar 22 persen pesantren yang secara konsisten menjalankan pendidikan karakter dan spiritual sebagai pusat utama kurikulum dan aktivitas. Sisanya lebih menekankan aspek akademik, wirausaha, dan pengembangan fasilitas fisik.
Dari sisi jumlah pesantren dan santri, Indonesia mencatat kemajuan besar. Menurut data Kementerian Agama, pada tahun 1970, jumlah pesantren di Indonesia sekitar 6.000 dengan jumlah 1,5 juta santri. Menjelang tahun 2000, jumlah pesantren meningkat menjadi lebih dari 11 ribu dengan jumlah santri lebih dari 2,5 juta. Kemudian, pada tahun 2024, jumlah pesantren melonjak hingga mencapai lebih 36 ribu pesantren, dengan lebih dari 5 juta santri.
Sayangnya, peningkatan kuantitas ini tidak selalu seiring dengan peningkatan kualitas ruhaniyah. Bahkan, kini, muncul banyak kesaksian dan komplain bahwa banyak santri 'terjebak'dalam sistem pendidikan yang mekanistik dengan disiplin kak dan minim relasi personal dengan kyai. Interaksi yang dulu bersifat tatap muka dan tatap hati, kini berubah menjadi tatap layar dan tatap kurikulum.
Di Mana Cahaya, Di Mana Cita-Cita?
Pesantren sejatinya adalah tempat menebar cahaya—yakni cahaya Ilahi yang menyinari akal dan hati para santri. Di lembaga pendidikan itu, para santri seharusnya diajarkan untuk mencintai ilmu karena Allah, hidup sederhana, berjuang dengan sabar, serta mengamalkan agama dalam kehidupan nyata. Cahaya itu adalah manifestasi dari nilai-nilai tauhid, keikhlasan, akhlak mulia, dan keberanian untuk menegakkan kebenaran.
Namun saat ini, cahaya itu mulai redup. Fenomena ini terjadi akibat semakin kabur orientasinya. Kini, tidak sedikit pesantren yang terlalu sibuk membangun gedung, mencari investor, memperluas usaha kuliner atau travel haji-umrah, tapi lalai menjaga kualitas pengajaran Alquran, ilmu adab, dan latihan spiritual.
Cita-cita luhur untuk membentuk insan kamil—manusia paripurna yang utuh secara iman dan ilmu—mulai terkikis. Dalam banyak kasus, santri justru dilatih menjadi pekerja, bukan pemimpin. Diajar menjadi penghafal, bukan pemikir. Didorong menjadi pengusaha, bukan penebar nilai.
Antara Cuan dan Keberkahan
Dalam konteks pendidikan masa kini, kita tidak menolak peran cuan (uang atau ekonomi). Namun cuan harus dimaknai sebagai sarana, bukan tujuan utama. Jika cuan menjadi pusat orientasi, maka seluruh sistem pendidikan akan ikut terdikte: kurikulum dibuat agar menarik pasar, bukan mencerdaskan jiwa; fasilitas diperbanyak demi gengsi, bukan untuk kebermanfaatan; guru dipilih karena terkenal, bukan karena kapasitas moral dan spiritual. Maka pesantren akan kehilangan keberkahannya. Sebab keberkahan bukan berasal dari seberapa besar uang yang mengalir, tapi seberapa ikhlas perjuangan dan seberapa lurus tujuan.
Terkait cuan, perlu juga dicatat bahwa pesantren juga tidak boleh terus-menerus menggantungkan 'nasibnya' dari cuan hasil donasi atau infak saja. Oleh karena itu, pesantren harus terus berinovasi dan menempuh cara-cara kreatif untuk meraih kemandirian finansial untuk menghidupi ribuan santri, guru, dan kegiatan sosial lainnya.
Menuju Reorientasi: Solusi Masa Depan Pesantren
Agar pesantren tidak terjebak dalam jebakan komersialisasi, perlu ada reorientasi besar yang menyentuh akar sistem: visi, nilai, dan tata kelola. Reorientasi dapat dilakukan melalu beberapa strategi sebagai berikut.
Pertama, pesantren harus kembali ke filosofi dasar pendiriannya yaitu li i‘la’i kalimatillah—meninggikan kalimat Allah melalui pendidikan jiwa, akal, dan amal. Ini harus menjadi rujukan utama setiap pengambilan kebijakan, termasuk dalam bidang ekonomi dan pengembangan usaha.
Kedua, pesantren harus memisahkan fungsi bisnis dan pendidikan. Setiap pesantren perlu membangun unit usaha yang dikelola secara profesional, baik oleh koperasi alumni atau pun yayasan terpisah. Dalam hal ini perlu ada sebuah pedoman tata kelola dan kode etik agar jangan sampai pesantren menjadi perusahaan, dan para kiai menjadi manajer keuntungan. Fokus pendidikan harus tetap berada di tangan para Asatidz (pengajar) yang berintegritas spiritual.
Ketiga, pesantren harus mengaudit visi dan nilai serta programnya secara berkala. Oleh karena itu pesantren memerlukan dewan etik atau lembaga pengawas independen yang secara berkala mengevaluasi apakah sebuah pesantren masih menegakkan visi awalnya. Dalam hal ini pemerintah dan masyarakat perlu dilibatkan sebagai bagian dari kontrol sosial dan moral.
Keempat, pesantren perlu terus memperkuat Kurikulum Adab dan Spiritual. Cahaya pesantren hanya bisa dipertahankan jika kurikulumnya tetap menyentuh dimensi adab, dzikir, latihan jiwa, dan keteladanan. Kajian kitab kuning, halaqah, muhasabah, dan bimbingan ruhani harus tetap menjadi tulang punggung pendidikan santri.
Kelima, dukungan terhadap pesantren kecil yang belum mandiri secara finansial. Banyak pesantren kecil yang justru lebih murni menjaga nilai dan tradisi. Mereka perlu mendapat dukungan—baik dalam bentuk dana hibah, pelatihan manajemen, atau kemitraan program—agar bisa bertahan di tengah arus kapitalisme pendidikan.
Mencari Jalan Tengah yang Bijak
Masa depan pesantren berada di persimpangan yang kritis. Di satu sisi, mereka harus bertahan hidup dan berkembang di dunia modern yang penuh tuntutan. Di sisi lain, mereka tidak boleh kehilangan ruh pendirian mereka: membina insan yang bertakwa, cerdas, dan berbudi luhur.
Oleh karena itu yang dibutuhkan bukanlah penolakan terhadap modernisasi, tapi keseimbangan antara cahaya dan cuan, antara nilai dan nilai tukar, antara cita-cita dan kenyataan.
Pesantren bukan hanya tempat menuntut ilmu, tapi tempat menumbuhkan makna hidup. Apabila pesantren berhasil menjaga cahaya ilahi sebagai kompas, menjadikan cuan sebagai bahan bakar yang halal dan proporsional, serta menghidupkan kembali cita-cita luhur dalam setiap langkah, maka pesantren tidak hanya tetap relevan, tetapi akan menjadi pilar utama kemajuan peradaban bangsa kita.

 3 months ago
119
3 months ago
119