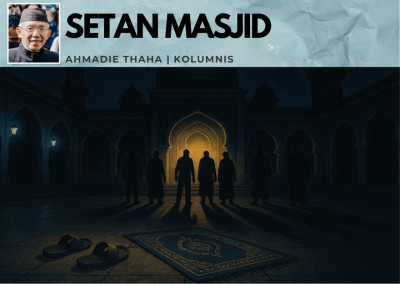REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Fajri M. Muhammadin (Dosen Departmen Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada; Divisi Riset dan Pengembangan, INSANIA: Asosiasi Pengkaji Islam dan Hukum Humaniter Internasional)
Di tengah makin memuncaknya genosida sejak 7 Oktober 2023 lalu, telah banyak datang kecaman bertubi-tubi terhadap israel. Mulai dari akar rumput, negara-negara, hingga berbagai organ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) termasuk Mahkamah Internasional dan Majelis Umum. Tentu saja, genosida israel terhadap rakyat Palestina praktis tidak terhambat berkat dukungan berbagai negara yang mengalirkan dana, logistik, dan persenjataan pada negara zionis tersebut.
Baru saja seperti ada sehembus angin dari rencana beberapa negara untuk mengakui negara Palestina, antara lain: Inggris, Kanada, dan Australia. Belum selesai kita memperdebatkan apakah rencana pengakuan itu akan benar terjadi dan apakah akan berdampak konkrit menyelesaikan konflik dibandingkan syarat-syarat yang akan diminta pada Palestina. Ternyata, sebuah ‘bom’ lain jatuh dari PBB.
Tanggal 30 Juli 2025, dalam konferensi PBB Bernama UN High-Level International Conference on the Two-State Solution yang diadakan di New York dan dihadiri oleh utusan dari hampir 130 negara, dikeluarkan dokumen baru yaitu UN Declaration on the “Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State Solution.” Singkatnya, kita sebut saja Deklarasi New York.
Dalam banyak hal, dokumen ini mengulangi banyak hal yang sama saja sejak bertahun atau bahkan berdekade lalu. Harapan untuk mengakhir konflik, ketaatan terhadap hukum internasional, mengecam israel, solusi dua negara, dan lainnya. Bukannya salah, justru yang heran adalah kenapa hal-hal seperti ini sudah disuarakan sejak zaman saya belum lahir sampai sudah jadi dosen begini kok masih belum selesai masalahnya.
Tentu juga, ada penekanan terhadap solusi dua negara. Solusi dua negara ini sebenarnya adalah legitimasi kezaliman, meskipun terlihat seperti alternatif pragmatis yang lebih baik daripada status-quo. Solusi dua negara ini bukan hal baru, dan sudah pernah saya kritik di tulisan saya yang lain.
Akan tetapi, ada tiga hal yang dapat dikatakan baru.
Kecaman Masal Terhadap Aksi Hamas pada 7 Oktober 2023
Pada Butir 4 Deklarasi New York, tertulis antara lain “We condemn the attacks committed by Hamas against civilians on the 7th of October” (Kami mengecam serangan Hamas terhadap rakyat sipil pada 7 Oktober).
Sebelumnya memang ada beberapa negara yang mengecam Hamas karena operasi 7 Oktober 2023. Tapi, ini pertama kali terjadi kecaman terhadap Hamas dalam skala PBB dan oleh banyak negara termasuk negara-negara Arab dan mayoritas Muslim (termasuk Indonesia).
Di satu sisi, mungkin kita bisa memberi sedikit prasangka baik jika lebih teliti memeriksa konstruksi kalimat tersebut. Bukan operasi militer 7 Oktober yang dikecam, melainkan sekadar dampaknya pada rakyat sipil saja. Dipahami dengan mafhum mukhalafah, berarti mayoritas operasi 7 Oktober tersebut (militer yang menjadi sasaran) tidak turut terkecam.
Di sisi lain, prasangka baiknya ya mungkin sedikit saja. Ada setidaknya dua masalah besar pada Butir 4 Deklarasi New York.
Pertama, dalam Butir 4 tersebut, kalimat yang saya kutipkan di atas dilanjutkan dengan “We also condemn the attacks by [i]srael against civilians in Gaza…” (Kami juga mengecam serangan oleh israel terhadap rakyat sipil di Gaza…). Sebenarnya kecaman terhadap israel tidaklah salah, bahkan sangat perlu meskipun sudah sangat berulang-ulang di berbagai dokumen PBB yang lain. Masalah ada pada draftingnya. Mengapa para drafter merasa lebih penting untuk mengecam Hamas terlebih dahulu sebelum “…kami juga mengecam…” israel?
Kedua, yang terpenting, seberapa besarkah skala serangan terhadap rakyat sipil oleh Hamas pada 7 Oktober sampai penting untuk disebutkan lebih dulu? Kita akui ada beberapa warga sipil yang turut menjadi sandera pada operasi militer Tawfan Al-Aqsa tersebut, dan Hukum Humaniter Internasional (cabang hukum internasional yang mengatur tentang jalannya konflik bersenjata) menjadikan hal tersebut sebagai kejahatan perang.
Akan tetapi, ada berapa yang seperti itu dibandingkan anggota aktif ‘tentara’ israel? Apakah sudah ada kajian oleh Lembaga independen dan imparsial mengenai berapa rakyat sipil yang benar menjadi korban akibat serangan Hamas, dan bukannya ditembak sendiri oleh israel sesuai Hannibal Directive? Apalah itu jika dibandingkan dengan genosida, penghancuran masif, dan ‘wabah’ kelaparan yang diakibatkan oleh zionis yang berdampak pada jutaan rakyat Gaza? Belum lagi, menimbang wajib militer bagi seluruh ‘rakyat’ israel dan kepemilikan senjata api oleh ‘sipil’ israel yang signifikan meningkat di tahun-tahun belakangan?
Hukum Humaniter Internasional memang memberikan batasan-batasan kekerasan yang dibenarkan dalam perang, demi melindungi rakyat sipil dan pihak-pihak lain yang tidak terlibat perang. Akan tetapi, batasan-batasan tersebut agak lentur karena mempertimbangkan kepentingan militer. Apalagi dalam kondisi yang sangat asimetrik, yaitu ketika terjadi ketimpangan yang sangat signifikan antara para pihak yang saling berperang (militer, ekonomi, sumberdaya lainnya).
Di perang asimetrik inilah Hukum Humaniter Internasional dan aktor-aktor “penghakim” seringkali kurang sensitif ketika menilai pihak-pihak yang memiliki banyak keterbatasan pilihan untuk melawan. Terutama dalam kasus Palestina ini, sangat sedikit pilihan cara Hamas untuk melawan penjajah Palestina secara signifikan. Seakan-akan Hukum Humaniter Internasional, setelah gagal mencegah pasukan israel melakukan kerusakan masif di Palestina, sekaligus melarang Palestina untuk melawan? Saya pernah mengulas masalah Hamas, Hukum Humaniter Internasional, dan perang asimetrik bersama Kirana Anjani di artikel saya yang lain.
Dengan demikian, sangat tidak proporsional untuk menyalahkan Hamas di forum publik dan besar seperti PBB apalagi sampai seakan mendahulukan kecaman ke Hamas daripada israel seperti ini.
Menuntut Hamas Untuk Melucuti Persenjataannya
Butir 11 Deklarasi New York berbunyi antara lain: “In context of ending the war, Hamas must end its rule in Gaza and hand over its weapons to the Palestinian Authority…” (Dalam konteks untuk menghentikan perang, Hamas harus mengakhiri kuasanya di Gaza dan menyerahkan senjatanya pada Otoritas Palestina).
Ini juga sebenarnya bukan hal yang sebaru itu, karena telah disinggung oleh beberapa negara sebelumnya (tentu terutama oleh israel). Tapi, ini pertama kalinya ia disebutkan di dokumen PBB yang didukung banyak negara sekaligus. Padahal ia sangat bermasalah.
Pertama, rasanya sangat keji, bahkan gila, bagi forum seperti PBB untuk menuntut pejuang kemerdekaan melucuti senjatanya ketika penjajahnya masih sangat ada, sangat bersenjata, dan sangat aktif menggunakannya. Penting dicatat bahwa, meskipun Butir 11 di atas ditempatkan di antara langkah-langkah pasca perang setelah Butir 8 yang berisi penghentian perang, frasa “In context of ending the war…” nampak menyiratkan bahwa pelucutan senjata Hamas ini dilakukan untuk mengakhiri (bukan setelah berakhirnya) perang.
Sedihnya, turut mendukung tuntutan ini, perwakilan Indonesia yang bangsanya pernah pada tanggal 9 November 1945 mengalami ultimatum untuk menyerahkan senjata oleh penjajah. Saat itu, pejuang kemerdekaan Indonesia memilih menolak menyerahkan senjata dan hanya menyerahkan pelurunya saja dan itupun lewat tembakan moncong senjata.
Adakah tuntutan bagi israel untuk melucuti senjatanya? Atau setidaknya mengurangi militernya? Tidak. Yang ada hanya tuntutan untuk berhenti menyerang, yang juga dituntutkan pada Hamas.
Kedua, lalu siapa yang diberikan otoritas untuk mengambil senjata tersebut? Menurut Butir 11 Deklarasi New York: Otoritas Palestina. Memang ada masanya ketika gerakan Fattah cukup kuat dalam memberikan perlawanannya, dan merekalah yang lebih menguasai wilayah Tepi Barat sekarang dan mendominasi Otoritas Palestina. Tapi, bagaimana prestasi mereka sekarang dalam mempertahankan Palestina secara fisik?Sepertinya mereka kesulitan mencegah invasi dari para pemukim zionis yang makin banyak merampok wilayah Tepi Barat. Bahkan, dilaporkan beberapa insiden para pejuang kemerdekaan yang justru disita senjatanya dan ditangkap atau dibunuh oleh Otoritas Palestina. Seriuskah, mau menyerahkan senjata pada mereka?
Ketiga, apakah tidak ganjil memaksa Hamas untuk berhenti memerintah Gaza seperti, ditambah juga bahwa Butir 13 menyebutkan juga bahwa sebuah komite administratif transnasional akan dibentuk untuk memerintah Gaza di bawah Otoritas Palestina. Padahal Butir 22 menuntut harus adanya pemilihan umum. Perlu diingat bahwa Hamas sudah pernah memenangkan pemilihan umum sebelumnya (tahun 2006) dan kini masih lebih populer dibandingkan Fattah dan Mahmoud Abbas yang sekarang menjabat presiden.
Rasanya sangat aneh untuk secara serta merta memaksa menghilangkan peran politik sebuah aktor yang sangat penting dan populer di israel. Apalagi kemudian Mahmoud Abbas belum lama menyatakan bahwa Hamas dan tokoh-tokohnya tidak akan dilibatkan di dalam pemilihan umum. Apakah seperti ini caranya pemilihan umum yang adil? Sedangkan apabila Hamas sebagai partai atau tokoh-tokohnya kelak memenangkan pemilihan umum tersebut, apakah ada jaminan israel tidak akan bertingkah lagi?
Pasukan Misi Stabilisasi Internasional
Barangkali ini salah satu tawaran yang cukup menarik dalam Deklarasi New York, meskipun prospeknya agak membuat memicingkan mata, adalah mekanisme pasca gencatan bersenjata permanen.
Butir 8-17 Deklarasi New York menuntut dilakukan beberapa langkah, yang dapat diringkas sebagai berikut: (1) berhenti berperang, tawanan kedua belah pihak dilepaskan, dan israel menarik mundur pasukannya dari Gaza, (2) masuknya bantuan kemanusiaan tanpa batasan, (3) pembentukan komite administrasi transnasional, dan (4) pembentukan Misi Stabilisasi Internasional. Sedangkan Misi Stabilisasi Internasional (Butir 15-16) adalah sejenis pasukan perdamaian yang sementara akan bertanggungjawab untuk mengamankan rakyat Palestina dan secara perlahan membantu membangun satuan keamanan milik Otoritas Palestina.
Akan tetapi, ada beberapa hal yang patut dipertanyakan.
Pertama, apakah misi ini dapat memiliki jumlah personel dan kapasitas persenjataan yang memadai? Misi PBB di Lebanon, misalnya, lumayan rajin kena tembak. Apalagi tidak ada tuntutan bagi israel untuk melucuti atau setidaknya mengurangi persenjataan. Berkaca juga pada insiden pembantaian Srebrenica tahun 1995, pasukan perdamaian PBB tidak mampu mencegah pembantaian Muslim Bosnia oleh tentara Serbia karena tidak memiliki persenjataan dan jumlah personel yang memadai. Belum lagi membahas genosida di Rwanda, di mana Pasukan Perdamaian PBB datang terlambat dan juga tidak mampu menghentikan pembantaian-pembantaian di depan mata mereka.
Kedua, apakah masalah keamanan di Palestina utamanya adalah masalah keamanan dari ancaman internal? Di Butir 16 Deklarasi New York disebutkan di antara tugas utama Misi Stabilisasi Internasional: “…support transfer of internal security responsibilities to the Palestinian Authority, provide capacity building support for the Palestinian State and its security forces…” (…mendukung peralihan tanggungjawab keamanan internal pada Otoritas Palestina, menyediakan dukungan peningkatan kapasitas bagi Negara Palestina dan satuan keamanannya…).
Bagaimana dengan kebutuhan Palestina untuk sebuah angkatan bersenjata untuk melindungi dari ancaman eksternal, sebagaimana memang masalah yang dialami Palestina sejak berpuluh-puluh tahun lamanya? Kita pahami bahwa lazimnya “satuan keamanan” untuk menghadapi “ancaman internal” biasanya memiliki jumlah personel dan kapasitas persenjataan yang jauh di bawah sebuah angkatan bersenjata.
Ketiga, bagaimana Misi Stabilisasi Internasional akan berperan di wilayah-wilayah terokupasi? Sebenarnya seluruh daratan yang diklaim sebagai israel, bahkan menurut garis 1967, adalah wilayah jajahan yang tidak sah dimiliki oleh israel. Tapi pun mau menuruti garis 1967, masih banyak wilayah yang semestinya milik Palestina tapi diduduki oleh pemukim liar zionis dan didukung oleh pasukan israel.
Sudah ada Resolusi Majelis Umum PBB dan Fatwa Mahkamah Internasional dari tahun 2024 yang menegaskan kewajiban israel untuk mengosongkan pemukiman-pemukiman liar tersebut dan mengembalikannya ke Palestina. Dasar hukum sudah ada, dan Deklarasi New York pun menyinggung garis 1967. Jadi, ketika disebutkan perlunya dibentuk sebuah pasukan Misi Stabilisasi Internasional, saya sudah berharap melihat bagaimana mereka akan diperankan dalam wilayah-wilayah terokupasi itu.
Ternyata nihil, dan saya pun kecewa meskipun tidak terkejut.
Keempat, yang terpenting di sini, masalah terbesar dari rencana Misi Stabilisasi Internasional ini adalah karena ia akan didirikan setelah berhentinya perang. Masalahnya, upaya apa yang dilakukan untuk menghentikan perang? Mengecam dan menuntut? Sudah berulangkali sampai bosan meskipun harus dilakukan terus, tapi apa konkritnya? Berapa kali israel sudah melanggar gencatan bersenjata (dan sekian banyak Resolusi PBB lainnya), yang sama sekali tidak disinggung di Deklarasi New York?
Jika memang PBB memiliki political will untuk mengirimkan sebuah pasukan internasional seperti ini, maka justru ia dibutuhkan untuk menghentikan perangnya. Kalau menunggu perang selesai dulu, apakah berarti menunggu rakyat Palestina harus habis dulu?
Lalu, Apa Yang Baru?
Apakah dapat dikatakan bahwa dunia mulai perlahan melemahkan lagi posisi Palestina? Terlebih lagi, yang mendukung butir-butir kejam ini ternyata termasuk negara-negara yang sebelumnya diharapkan untuk menjadi yang terdepan membela Palestina. Saya ingin sekali mengatakan: tidak.
Tapi, terhadap israel, banyak kecaman dan tuntutan tapi tidak ada yang baru. Ia hanya mengulang saja kecaman dan tuntutan sebelum-sebelumnya saja. Sedangkan terhadap Palestina, sepertinya hanya tiga hal yang baru dari Deklarasi New York: (a) kecaman dan (b) pelemahan terhadap satu-satunya entitas yang konkrit memperjuangkan kemerdekaan Palestina di lapangan, serta (c) janji yang lemah dan nyaris mustahil untuk terlaksana sama sekali.
Hamas dan para faksi pejuang lain (yang sepertinya sama sekali dilupakan dalam Deklarasi New York) menyambut positif Deklarasi New York tersebut. Meskipun, tentunya, ada juga pernyataan Hamas yang secara tersirat menolak Solusi Dua Negara. Negosiasi memang sulit, dan kadang kompromi terpaksa dilakukan. Akan tetapi, makin sulitlah negosiasi ketika negara-negara yang seharusnya membela Palestina malah memasang harga yang rendah.

 2 months ago
79
2 months ago
79