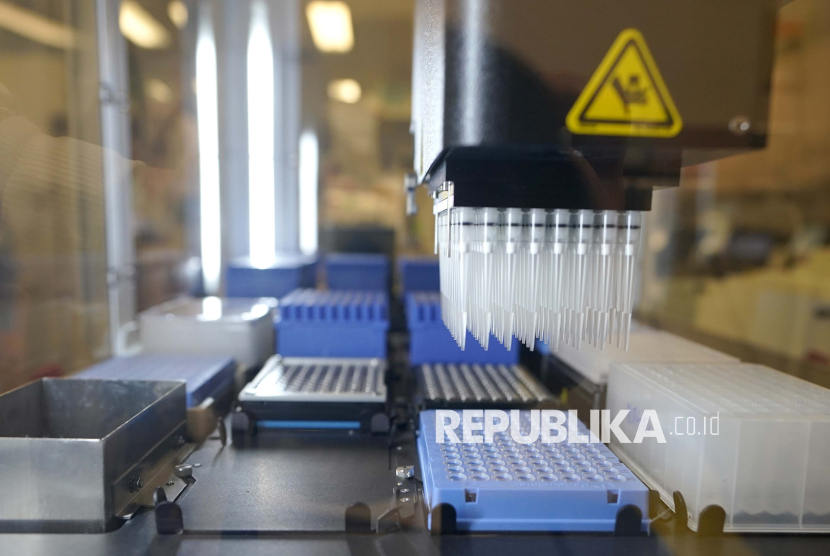REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai kebijakan beras satu harga bukan jawaban atas disfungsi tata niaga pangan yang sistemik. Masalah beras oplosan yang mencuat Juli 2025 disebut sebagai gejala dari lemahnya pengawasan mutu dan distribusi, serta minimnya reformasi kelembagaan.
“Skandal beras oplosan menjadi potret buruk tata niaga pangan,” kata Head of Center of Food, Energy, and Sustainable Development (FESD) Indef, Abra Talattov, dalam Monthly Update edisi Juli 2025 berjudul “Pasar Pangan Rawan Manipulasi, Subsidi Energi Rawan Membengkak”, Ahad (3/8/2025), di Jakarta.
Abra menyoroti hasil uji Kementerian Pertanian terhadap 268 merek beras, di mana 212 di antaranya (79 persen) melanggar standar mutu, terutama terkait kadar patahan dan pelabelan premium yang tidak sesuai. Ia menyebut praktik ini menyebabkan kerugian konsumen hingga Rp 99 triliun per tahun akibat asimetri informasi dan ketiadaan sistem kendali mutu.
“Kecurigaan publik terhadap hampir semua beras kemasan mendorong penurunan konsumsi beras premium dan anjloknya omzet sejumlah pedagang hingga 50 persen,” kata Abra.
Ia menambahkan, kasus ini menimbulkan ketidakstabilan pasar dan menyulut inflasi pangan. Di tengah pasokan nasional yang sebenarnya meningkat, harga beras justru naik di 219 kabupaten/kota pada pekan keempat Juli 2025 (data BPS), bahkan menembus Rp 54.772/kg di Papua.
Abra juga menyinggung dugaan penyalahgunaan beras subsidi dalam praktik oplosan, yang berpotensi mengalihkan alokasi dari kelompok rentan ke pasar komersial. Ketimpangan akses pangan pun kian dalam.
“Langkah penegakan hukum dan intervensi pasar memang tepat secara teknis, tapi sifatnya korektif, belum menyentuh akar struktural dari kegagalan tata kelola mutu pangan,” tegasnya.
Abra menilai pemerintah hanya menunjukkan respons reaktif, seperti pemeriksaan mutu beras, pemanggilan enam produsen besar, dan distribusi 4,2 juta ton stok Bulog. Namun belum ada langkah serius mereformasi standar nasional mutu beras, mekanisme sertifikasi, serta insentif dan sanksi untuk menegakkan disiplin pasar.
“Ketiadaan sistem pengawasan mutu yang konsisten membuat pasar beras nasional rentan terhadap praktik manipulatif,” ujar Abra. “Ketergantungan pada operasi pasar dan aparat hukum tidak bisa menggantikan reformasi institusional.”
Setelah terungkap masalah beras oplosan, pemerintah menetapkan kebijakan satu harga dan mutu, menghapus klasifikasi medium-premium dan menetapkan HET nasional Rp 12.500–13.500/kg. Tujuannya untuk menyederhanakan sistem harga dan menghapus celah manipulasi kualitas.
Namun menurut Abra, kebijakan ini bisa jadi bumerang. Tanpa insentif diferensiasi harga, produsen tak punya dorongan untuk mempertahankan mutu. Di sisi lain, biaya logistik wilayah timur tak bisa disamaratakan dengan kawasan barat.
“Sekitar 95 persen penggilingan padi adalah unit kecil-menengah. Mereka berisiko gagal memenuhi standar mutu baru jika tak mendapat dukungan investasi,” ujarnya.
Abra juga mengingatkan kebijakan satu harga berpotensi mendorong konsolidasi pasar oleh pelaku besar dan memukul konsumen miskin. Jika HET disetarakan dengan harga premium, konsumen berpenghasilan rendah yang biasa membeli beras medium bisa terdampak langsung. “Hal ini dapat meningkatkan risiko kemiskinan,” katanya.
Sebagai alternatif, FESD Indef mendorong pemerintah melakukan reformasi mutu dan regulasi lebih dulu ketimbang menyamaratakan harga. Di antaranya dengan mewajibkan SNI untuk beras konsumsi dan pelabelan yang transparan agar mutu produk bisa ditelusuri.
“Studi di Jepang menunjukkan sistem ini efektif menjaga kepercayaan konsumen dan mencegah manipulasi kualitas,” ujar Abra.
Indef juga menyarankan penggunaan skema harga fleksibel berbasis zonasi, bukan HET tunggal. Model ini sudah diterapkan dalam Perbadan No. 7/2023 dan terbukti menjaga pasokan di wilayah berbiaya tinggi seperti Papua dan Maluku.
“Studi di Filipina menunjukkan, price ceiling nasional justru bisa menurunkan mutu dan mendorong pasar gelap bila tidak disesuaikan dengan struktur biaya,” jelasnya.
Abra menekankan, jika kebijakan penyeragaman tetap diterapkan, pemerintah harus menyediakan fase transisi dengan evaluasi dampak sosial ekonomi secara berkala. “Itu penting untuk menjaga kepercayaan pelaku pasar,” katanya.

 2 months ago
65
2 months ago
65