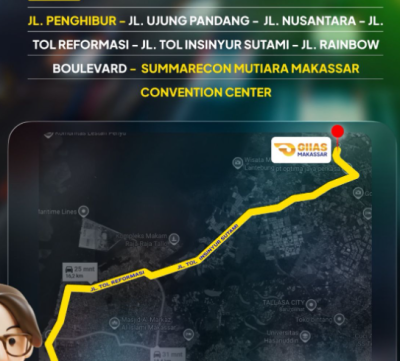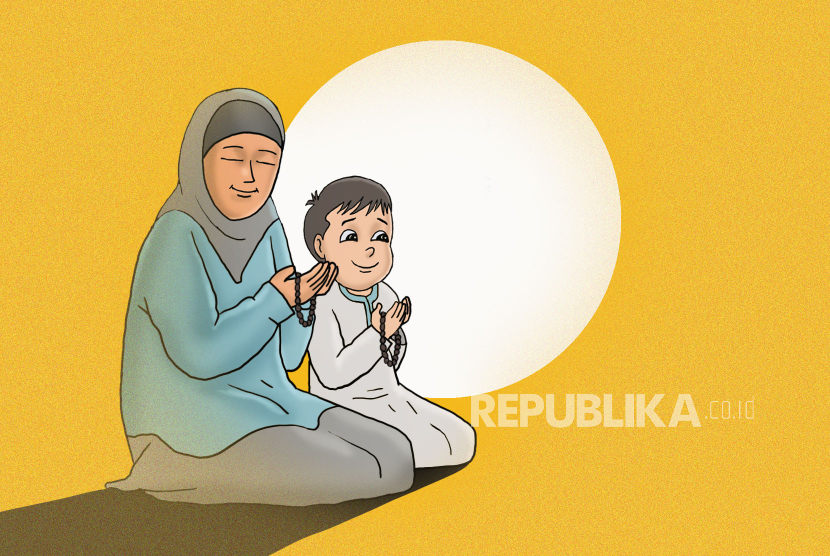Dhama Maulana
Dhama Maulana
Sastra | 2025-09-06 02:08:24
 cerita ini adalah sisipan cerita studi Aziz dari judul cerpen pertamaku yang berjudul Benang Cinta di Balik Toga
cerita ini adalah sisipan cerita studi Aziz dari judul cerpen pertamaku yang berjudul Benang Cinta di Balik Toga
Langit Amsterdam sore itu tampak kelabu, seolah ikut merasakan hati Aziz yang sedang diliputi kegelisahan. Di balik tumpukan jurnal dan laptop yang menyala, pikirannya tak lagi fokus pada pembelajarannya di kelas, Sudah dua minggu ia tidak mendengar kabar dari Ibu Salma, ibunya di kampung halaman. Biasanya, meski hanya pesan singkat, ibunya tak pernah absen mengirim doa dan semangat. Tapi kali ini, layar ponselnya kosong, dan itu membuat dada Aziz terasa sesak.
“Hé Aziz! Luister je niet naar me? Ga nu uit mijn les, ik wil je deze week niet zien”. (hei Aziz! kau tidak mendengarkanku? sekarang pergi dari kelasku, aku tidak ingin melihatmu pekan ini). Ucap prof. Diderik memecah lamunan Aziz di kelas dan langsung pergi meninggalkan kelas.
Aziz duduk termenung di halte tram, menatap kosong ke arah jalanan yang basah oleh hujan ringan. Suara Prof. Diderik masih terngiang di telinganya, tapi yang lebih mengganggu adalah suara hatinya sendiri. Ia teringat masa-masa sebelum keberangkatannya ke Belanda, saat ia dan ibunya duduk berdua di ruang tamu kecil yang hanya diterangi lampu gantung tua. Malam itu, Ibu Salma menyuguhkan teh hangat dan berkata
“Nak, Ibu nggak punya apa apa buat bekal kamu ke sana. Tapi Ibu punya doa, dan itu nggak akan pernah berhenti.” Ucap bu Salmah kepada anaknya sebelum ia berangkat melanjutkan studinya ke Belanda
Malam itu adalah malam yang penuh haru. Aziz memeluk ibunya erat, merasakan tubuh yang mulai rapuh namun tetap hangat. Ia ingat betul bagaimana ibunya menyembunyikan air mata di balik senyum, saat melepas anaknya pergi ke negeri jauh demi mimpi yang besar.
“Kalau kamu sukses nanti, jangan lupa pulang ya, Nak. Ibu nggak butuh apa-apa, cuma pengen lihat kamu bahagia,” ucapnya pelan. Aziz mengangguk, berjanji dalam hati bahwa ia akan membalas semua pengorbanan itu.
Kini ia hanya bisa mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa mungkin ibunya hanya sibuk atau lupa mengisi pulsa. Namun, rasa khawatir itu tak bisa dibendung. Di negeri orang, dengan jarak ribuan kilometer dari rumah, Aziz merasa kecil dan tak berdaya. Ia teringat janji yang pernah ia tulis di secarik kertas bertahun lalu “Jangan pernah mengecewakan setiap keringat Ibu yaa.”
Beberapa hari setelah kejadian di kelas, ketika Aziz sedang perjalanan pulang dari kampus menuju apartmentnya, ia di panggil oleh tetangganya yang Bernama Arnoud
“Bro, net kwam er een postbode naar me toe om het aan je te geven” (bro, tadi ada tukang pos datang kepadaku untuk memberikannya kepadamu) ucap tetangganya kepada Aziz sembari membuka tas dan memberikan surat itu kepada Aziz
“Dank je wel bro, als ik vragen mag, waar is deze brief vandaan?” (terimakasih bro, kalau boleh tau ini surat dari mana?) ucap Aziz kepada Arnoud karena ia bingung
“Ik weet het niet, misschien uit Indonesië. De postbode vertelde me dat” (entahlah, mungkin dari indonesia. pak pos memberitahukannya seperti itu) balas Arnoud
“Oké, bedankt” (baiklah, terimasih) ucap Aziz sambil pergi ke apartmennya
Aziz menerima sebuah amplop lusuh yang dikirim dari Indonesia yang di titipkan tukang pos kepada temannya. Ia sempat bingung, siapa yang masih mengirim surat di zaman serba digital ini? Namun saat melihat nama pengirimnya, “Bu Rini Semanggi II”, jantungnya berdetak lebih cepat. Tangannya gemetar saat membuka surat itu, dan matanya langsung tertuju pada baris pertama.
Aziz, Nak Maaf Ibu Rini harus menyampaikan ini lewat surat. Ibumu, Bu Salma, sudah dua bulan terakhir sering sakit-sakitan. Tapi beliau selalu bilang, ‘Jangan kasih tahu Aziz, biar dia fokus belajar.’ Sekarang kondisinya makin lemah, dan kami khawatir
Isi surat itu membuat Aziz berdetak dengan, Aziz tak sanggup membaca lebih jauh. Surat itu jatuh ke lantai, dan ia hanya bisa menatap kosong ke luar jendela apartemennya. Hatinya seperti diremas. Ia merasa seperti anak durhaka,terlalu sibuk mengejar gelar, hingga lupa bahwa waktu bersama ibu tak bisa diulang. Ia berdiri, mengambil ponsel, dan memesan tiket pulang tanpa pikir panjang. Kali ini, ia tak peduli pada riset, nilai, atau gelar. Ia hanya ingin pulang. Pulang untuk ibunya.
Aziz menatap layar laptopnya dengan mata yang mulai memerah, jantungnya berdegup tak karuan. Ia sudah memilih tanggal, maskapai, dan rute tercepat menuju Indonesia sebuah perjalanan yang ia harap bisa menjadi pelarian dari rasa bersalah yang mulai menghantuinya. Namun saat hendak menyelesaikan pembayaran, muncul notifikasi dari sistem kampus yang terasa seperti tamparan keras
Mahasiswa penerima beasiswa penuh tidak diizinkan meninggalkan negara studi sebelum menyelesaikan program, kecuali dalam keadaan darurat yang telah disetujui oleh pihak sponsor dan pemerintah.
Aziz membeku. Dunia seolah berhenti berputar. Ia mencoba menghubungi pihak kampus, lalu kedutaan, berharap ada celah, ada belas kasih. Namun jawabannya sama saja ia harus menyelesaikan studinya terlebih dahulu.
“Kami memahami kekhawatiran Anda, tetapi aturan ini bersifat ketat dan tidak bisa dinegosiasikan,” ucap petugas dengan nada formal yang dingin, seolah tak menyisakan ruang bagi rasa kemanusiaan.
Aziz menutup telepon dengan tangan gemetar, matanya kosong menatap dinding kamar yang kini terasa sempit dan menyesakkan. Ia merasa seperti terjebak di antara dua dunia satu yang menuntutnya untuk sukses demi masa depan, dan satu lagi yang memanggilnya pulang dengan air mata dan doa yang mungkin tak sempat terkabul. Di kamar kecil itu, ia duduk di lantai, memeluk lututnya, mencoba menahan tangis yang tak lagi bisa dibendung. Ia teringat wajah ibunya, senyum yang selalu ia rindukan, dan suara lembut yang dulu berkata, Nak, Ibu nggak butuh apa-apa, cuma pengen lihat kamu bahagia. Kini, kebahagiaan itu terasa jauh, dan Aziz hanya bisa berbisik lirih, dengan suara yang nyaris patah, “Ma kamu sembuh kan?” ucap Aziz dengan nada gontai
Beberapa hari berlalu sejak surat dari Bu Rini tiba, namun perasaan Aziz tak kunjung membaik. Ia kembali ke kampus, mencoba menjalani rutinitas seperti biasa, tapi langkahnya terasa berat dan pikirannya tak lagi utuh. Di kelas, ia duduk di barisan tengah, namun matanya tak pernah benar-benar menatap papan tulis. Suara dosen hanya menjadi gema samar di telinganya, tenggelam oleh suara hatinya yang terus bertanya Bagaimana keadaan Ibu sekarang? Apakah ia masih bisa berdiri? Masih bisa tersenyum? Lamunan itu begitu dalam hingga ia tak menyadari bahwa Prof. Diderik sudah berdiri tepat di depannya.
“Hé Aziz! Luister je niet naar me?” ucap sang profesor dengan nada tajam, membuat seluruh kelas menoleh. Aziz tersentak, matanya langsung menatap ke depan dengan gugup. “Ga nu uit mijn les, ik wil je deze week niet zien.” (Sekarang pergi dari kelasku, aku tidak ingin melihatmu pekan ini.)
Aziz hanya mengangguk pelan, mengemasi barang-barangnya tanpa berkata sepatah kata pun. Ia melangkah keluar dengan kepala tertunduk, merasa semakin jauh dari dirinya sendiri. Namun sebelum ia benar-benar meninggalkan gedung kampus, seorang asisten dosen menghampirinya dan berkata, “Prof. Diderik ingin bicara denganmu setelah kelas selesai. Katanya penting.” Aziz hanya mengangguk lagi, kali ini dengan rasa cemas yang tak bisa ia jelaskan. Ia tahu, mungkin waktunya telah tiba untuk menjelaskan semuanya tentang ibunya, tentang rasa bersalah, dan tentang mimpi yang kini terasa seperti beban.
Sore itu, setelah kelas berakhir dan kampus mulai sepi, Aziz melangkah pelan menuju ruang tempat Prof. Diderik menunggunya. Langkahnya terasa berat, bukan karena lelah fisik, tapi karena beban batin yang tak kunjung reda. Ia tak tahu harus berkata apa, tak tahu apakah profesor itu akan memahami apa yang sedang ia rasakan. Saat pintu diketuk, suara berat dari dalam menyuruhnya masuk. Prof. Diderik duduk di balik meja kerjanya, menatap Aziz dengan sorot mata yang tak lagi tajam seperti di kelas tadi.
“Aziz, duduklah,” ucapnya pelan, berbeda dari nada biasanya. Aziz duduk dengan gugup, menunduk, dan mencoba menahan gejolak emosi yang sudah mengendap berhari-hari.
“Saya tahu kamu bukan mahasiswa yang malas atau tidak peduli. Tapi akhir-akhir ini kamu seperti orang yang hilang arah. Ada apa?” tanya sang profesor, kali ini dengan nada yang lebih manusiawi.
Aziz terdiam sejenak, lalu mulai bercerita tentang surat dari kampung, tentang ibunya yang sakit, tentang larangan pulang dari pihak kampus dan sponsor. Kata-kata itu keluar perlahan, diselingi jeda panjang dan suara yang bergetar. Prof. Diderik mendengarkan dengan tenang, sesekali mengangguk, dan akhirnya berkata,
“Weet je, Aziz... soms is de academische wereld te rigide om de meest menselijke dingen te begrijpen. Maar je bent hier tenslotte gekomen vanwege je moeder, en nu moet je weg omdat je moeder niet je buurvrouw is“(Kamu tahu, Aziz kadang dunia akademik terlalu kaku untuk memahami hal-hal yang paling manusiawi. Tapi bagimanapun kau datang kesini karena ibumu dan sekarang harus pergi dari sini harus karena ibumu bukan tetanggamu.) Aziz terdiam cukup lama setelah mendengar kalimat itu. Kata kata Prof. Diderik menamparnya dengan lembut bukan karena marah, tapi karena jujur. Ia sadar, selama ini ia terlalu larut dalam rasa bersalah dan ketakutan, hingga lupa bahwa keputusan besar dalam hidupnya tak boleh didasarkan pada kabar yang belum pasti. Ia datang ke negeri ini karena ibunya, karena doa dan pengorbanan yang tak pernah berhenti mengalir dari perempuan itu. Maka jika ia harus pergi, seharusnya bukan karena desakan rasa panik atau kabar dari orang lain, tapi karena keyakinan bahwa ibunya memang membutuhkannya saat ini. Aziz menatap Prof. Diderik dengan mata berkaca-kaca, bukan hanya karena terharu, tapi karena untuk pertama kalinya sejak menerima surat itu, ia merasa benar benar didengarkan. Ada seseorang yang tidak hanya melihatnya sebagai mahasiswa, tapi sebagai anak yang sedang berjuang menjaga cintanya dari kejauhan.
Beberapa hari setelah pertemuan itu, Prof. Diderik mulai bergerak. Ia bukan tipe dosen yang mudah tergerak oleh cerita pribadi mahasiswa, tapi ada sesuatu dalam diri Aziz yang membuatnya merasa perlu turun tangan. Ia mulai menghubungi pihak sponsor beasiswa, menjelaskan situasi dengan nada yang tegas namun penuh empati. Mahasiswa ini bukan hanya aset akademik, tapi juga manusia yang sedang menghadapi krisis keluarga, tulisnya dalam surat elektronik yang ia kirim ke lembaga pemberi beasiswa. Tak cukup sampai di situ, ia juga mengajukan permohonan khusus kepada pihak kampus dan kedutaan, menyertakan surat dari tetangga Aziz sebagai bukti bahwa kondisi ibu Aziz memang mengkhawatirkan. Setiap hari, Aziz menunggu kabar dengan hati yang tak tenang. Ia tahu proses ini tidak mudah, dan mungkin tidak akan berhasil. Tapi melihat usaha Prof. Diderik, ia merasa ada harapan kecil yang mulai tumbuh di tengah gelapnya situasi. Di sela sela kegundahannya ia berencana akan mengirimkan surat karena ia tidak tahu no telepon ibu Arina Entah kapan, entah bagaimana, tapi ia akan pulang. Karena seperti kata Prof. Diderik, “Kau datang ke sini karena ibumu, dan jika kau harus pergi, maka itu pun harus karena ibumu.”
Hari-hari berlalu dengan harapan yang terus digantung di langit kelabu Amsterdam. Aziz menunggu dengan cemas, berharap ada kabar baik dari Prof. Diderik. Setiap langkah menuju kampus terasa seperti menapaki jalan yang tak pasti. Namun pada suatu sore, Prof. Diderik memanggilnya kembali ke ruang dosen. Wajah sang profesor tampak lebih serius dari biasanya, dan itu cukup untuk membuat jantung Aziz berdegup tak karuan.
“Aziz,” ucapnya pelan,
“Saya sudah mencoba semua jalur. Saya kirim surat ke sponsor, ke pihak kampus, bahkan ke kedutaan. Tapi semuanya nihil. Mereka tetap pada keputusan awal. Kamu tidak bisa pulang sebelum program selesai.” Lanjut prof. Diderik
Aziz terdiam. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam dadanya. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan air mata yang mulai menggenang. “Saya minta maaf,” lanjut Prof. Diderik, “Saya tahu ini tidak adil. Tapi saya harap kamu tetap kuat. Ibumu pasti ingin kamu menyelesaikan ini.”
Aziz mengangguk pelan, meski hatinya menjerit. Ia merasa seperti dikurung oleh mimpi yang dulu ia kejar dengan penuh semangat. Kini, mimpi itu berubah menjadi dinding yang memisahkannya dari orang yang paling ia cintai. Ia keluar dari ruangan itu dengan langkah gontai, membawa beban yang tak bisa ia bagi kepada siapa pun. Di kamar malam itu, ia menatap surat yang belum sempat ia kirim, lalu menambahkan satu kalimat di akhir "Bu, kalaupun kaki ini belum bisa pulang, hati ini sudah sampai di pangkuanmu sejak hari pertama aku tahu kau sakit. Tunggu Aziz, ya Bu. Jangan pergi dulu."
Setelah semua upaya untuk pulang menemui ibunya menemui jalan buntu, Aziz duduk termenung di balkon apartemennya, menatap langit Amsterdam yang mulai gelap. Dalam keputusasaan itu, muncul satu ide yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya Bagaimana jika Ibu yang datang ke sini? Bukan untuk berlibur, tapi untuk dirawat. Di negara yang memiliki fasilitas medis lebih lengkap, mungkin ada harapan lebih besar untuk kesembuhan ibunya.
Keesokan harinya, dengan semangat yang tersisa, Aziz menemui Prof. Diderik dan menyampaikan idenya. Sang profesor terdiam sejenak, lalu berkata, “Itu bukan hal mudah, Aziz. Tapi bukan berarti tidak mungkin.” Bersama-sama, mereka mulai menyusun surat permohonan kepada kedutaan dan pihak imigrasi, menjelaskan kondisi Ibu Salma dan alasan medis yang mendesak. Aziz juga menghubungi rumah sakit di Amsterdam, mencari tahu prosedur rujukan pasien dari luar negeri. Ia bahkan siap menanggung biaya pribadi jika memang harus.
Namun, jalan itu pun tidak mulus. Banyak dokumen yang harus disiapkan, termasuk surat keterangan medis dari Indonesia, visa khusus untuk perawatan, dan jaminan finansial. Di tengah proses itu, kondisi Ibu Salma dikabarkan semakin menurun. Waktu terasa seperti musuh yang tak bisa diajak kompromi. Aziz kembali dihantui pertanyaan yang sama Apakah semua ini akan cukup cepat? Atau justru sudah terlambat?
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.

 1 month ago
27
1 month ago
27