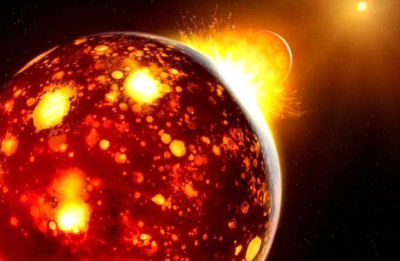Oleh : Mohammad Nur Rianto Al Arif, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setiap tahun, pembahasan mengenai biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) menjadi topik hangat di ruang publik Indonesia. Ketika pemerintah bersama DPR menetapkan biaya haji, muncul beragam pandangan dimana sebagian menilai kenaikan biaya sebagai keniscayaan akibat naiknya harga dan kurs, sementara sebagian lain menilai kebijakan itu belum adil karena terasa terlalu memberatkan jamaah.
Polemik ini kembali mengemuka pada penetapan biaya haji tahun 2026, di tengah perubahan lanskap ekonomi global, perpindahan pelaksanaan ibadah haji kepada Kementerian Haji dan Umrah, pengelolaan dana haji di bawah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), serta kekhawatiran masyarakat akan adanya risiko “skema ponzi” dalam sistem subsidi haji.
Tulisan ini mencoba menakar persoalan keadilan dalam penentuan biaya haji dengan pendekatan ekonomi dan tata kelola, sekaligus menawarkan gagasan baru tentang pola pengelolaan keuangan haji yang lebih berkeadilan, transparan, dan produktif.
Ibadah haji bukan hanya ritual spiritual, melainkan juga ekspresi kesetaraan sosial. Semua jamaah mengenakan pakaian ihram yang sama, berdiri sejajar di Arafah tanpa perbedaan status sosial. Namun, di balik kesetaraan simbolik itu, realitas ekonomi menunjukkan ketimpangan dalam akses beribadah. Biaya haji yang terus meningkat membuat sebagian masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah harus menunggu puluhan tahun untuk bisa berangkat.
Di Indonesia, porsi setoran awal haji sebesar Rp25 juta dan biaya pelunasan yang bervariasi setiap tahun menciptakan kesenjangan yaitu jamaah yang mampu menabung lebih cepat akan berangkat lebih awal, sementara jamaah lain hanya bisa berharap “giliran” yang makin panjang. Data Kementerian Agama menunjukkan antrean haji reguler di Indonesia bervariasi paling cepat 13 tahun dan paling lama hampir mencapai 40 tahun. Hal ini berarti calon jamaah yang mendaftar di usia 40 tahun, baru bisa berangkat di usia 70-an.
Kebijakan masa tunggu haji saat ini telah direvisi. Menurut Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa masa tunggu jemaah haji tiap provinsi kini sama, yakni 26 tahun. Pembagian kuota saat ini akan lebih berprinsip pada keadilan karena provinsi dengan jumlah pendaftar haji lebih banyak akan mendapat kuota lebih banyak.
Di titik ini, muncul pertanyaan etis yaitu apakah sistem pembiayaan haji kita saat ini sudah adil? Apakah subsidi dari dana kelolaan jamaah yang belum berangkat untuk menutupi kekurangan biaya jamaah yang berangkat kini sesuai dengan prinsip syariah dan keadilan antar generasi?
Pemerintah bersama komisi VIII DPR RI telah menyepakati besaran biaya haji tahun 2026 per jamaah sebesar RP 87,4 juta. Angka ini menurun sekitar Rp 2,89 juta dibandingkan dengan tahun 2025. Kemudian rata-rata bipih atau biaya yang dibayar per jamaah sebesar Rp 54,2 juta atau sebesar 62 persen dari keseluruhan BPIH. Sisanya sebesar Rp 33 juta atau 38 persen akan bersumber dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji.
Skema ini menunjukkan bahwa 38 persen biaya haji ditopang dari hasil investasi dana jamaah lain yang belum berangkat. Namun kondisi ini tidak selamanya dalam kondisi ideal, dimana ruang fiskal nilai manfaat hasil investasi BPKH terbatas. BPKH tidak bisa terus menutup kenaikan biaya dengan mengorbankan nilai manfaat yang mestinya juga menjadi hak jamaah di masa mendatang.
Pola inilah yang oleh sebagian pengamat ekonomi disebut akan berpotensi menyerupai “skema ponzi terselubung” yaitu jamaah yang berangkat saat ini dibiayai sebagian oleh jamaah yang belum berangkat. Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menuduh atas terjadinya praktik dengan skema ponzi, namun lebih kepada peringatan dini atas ketidakseimbangan struktural dalam sistem pembiayaan haji.
Istilah “skema ponzi” berasal dari nama Charles Ponzi, penipu legendaris yang menjanjikan keuntungan besar dari investasi fiktif dengan membayar investor lama menggunakan dana dari investor baru. Dalam konteks dana haji, situasinya memang berbeda secara fundamental dimana tidak ada niat penipuan, dan semua dana tercatat serta diaudit. Namun, mekanisme cross-subsidy antar generasi jamaah memiliki risiko serupa jika tidak dikelola secara hati-hati.
Tahun 2025, sekitar Rp 6,83 triliun nilai manfaat hasil pengelolaan dana haji digunakan untuk menutup selisih biaya haji jamaah yang berangkat. Padahal, dana pokok jamaah yang belum berangkat seharusnya tetap tumbuh untuk menjaga nilai manfaatnya di masa depan. Bila tren ini terus berlanjut akan berisiko pada keseimbangan antara jumlah jamaah yang berangkat dan yang menunggu bisa terganggu, dan pada akhirnya cadangan nilai manfaat akan menipis.
Laporan keuangan BPKH menunjukkan bahwa total dana kelolaan haji mencapai sekitar Rp170,5 triliun (per Juni 2025). Hingga Agustus 2025, sebesar 75,9 persen dana atau Rp130,39 triliun dialokasikan untuk investasi yang fokus pada sukuk, reksadana, investasi langsung, dan emas, sementara sisanya Rp41,39 triliun ditempatkan di instrumen likuid seperti deposito dan giro.
Namun pertanyaan yang muncul apakah imbal hasil yang diterima akan cukup untuk menutup kenaikan biaya haji akibat inflasi dan kurs riyal. Jika ketidakseimbangan ini terus dibiarkan, maka akan muncul risiko keberlanjutan yaitu jamaah di masa depan harus menanggung biaya jauh lebih besar karena subsidi hari ini menggerus nilai manfaat mereka.
Dalam memperluas peran strategisnya di luar negeri, BPKH membentuk anak perusahaan BPKH Limited di Arab Saudi. Perusahaan ini bergerak di sektor-sektor penting dalam ekosistem haji, termasuk perhotelan, properti, catering, dan transportasi. Namun, skala investasi ini masih kecil dibandingkan potensi dana yang ada.
Namun, tantangan terbesar BPKH adalah dilema antara likuiditas dan profitabilitas. Dana haji harus selalu siap cair untuk membiayai jamaah yang berangkat tiap tahun, sehingga penempatan di instrumen jangka panjang menjadi terbatas. Akibatnya, potensi imbal hasil tinggi dari investasi langsung sering tidak bisa dioptimalkan.
Selain itu, BPKH juga menghadapi tekanan persepsi publik. Setiap kali muncul isu penggunaan dana haji untuk investasi tertentu, publik sering curiga, padahal investasi produktif yang aman justru dibutuhkan agar nilai manfaat tumbuh. Di sini, penting bagi BPKH memperkuat komunikasi publik dan literasi keuangan syariah umat, agar pengelolaan dana haji dipahami sebagai bagian dari ekonomi ibadah, bukan komersialisasi ibadah.
Untuk menghindari ketergantungan pada instrumen keuangan semata, BPKH perlu memperluas investasi langsung di sektor-sektor yang relevan dengan haji dan ekonomi umat. Strategi ini punya dua keuntungan sekaligus yaitu menghasilkan imbal hasil finansial, dan mengurangi biaya operasional haji secara langsung.
Keadilan dalam ibadah haji harus dipahami tidak hanya antar jamaah dalam satu tahun, tetapi juga antar generasi. Keadilan horizontal berarti semua jamaah tahun yang sama membayar dengan prinsip proporsional. Tidak boleh ada yang membayar jauh lebih sedikit dari biaya riil karena disubsidi berlebihan.
Keadilan vertikal berarti jamaah di masa depan tidak menanggung akibat keputusan kebijakan hari ini. Jika nilai manfaat terus digunakan untuk subsidi saat ini, jamaah 10–20 tahun mendatang bisa kehilangan haknya untuk menikmati hasil investasi yang seharusnya mereka peroleh.
Prinsip ini sesuai dengan nilai Islam tentang amanah (trust). Dana haji bukan milik institusi, melainkan titipan jamaah. Maka keadilan diukur bukan dari “berapa murah biaya haji tahun ini”, tetapi dari “seberapa adil sistem itu bagi seluruh jamaah sepanjang waktu”.
Saat ini pemerintah tengah menyiapkan Pembangunan kampung haji. Hal ini pertama kali diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk upaya peningkatan pelayanan bagi jemaah haji asal Indonesia yang jumlahnya salah satu yang terbesar di dunia.
Untuk mencapai sistem yang adil dan berkelanjutan, penetapan BPIH perlu didasarkan pada prinsip rasional dan transparan. Setidaknya terdapat empat langkah yang dapat dilakukan. Pertama, keterbukaan struktur biaya. Publik harus tahu komponen biaya haji seperti transportasi udara, akomodasi, konsumsi, asuransi, hingga pelayanan kesehatan. Keterbukaan ini akan mengurangi kecurigaan dan meningkatkan kepercayaan.
Kedua ialah kebijakan berbasis data, bukan politik. Kenaikan biaya haji seharusnya didasarkan pada data kurs, inflasi, dan harga layanan, bukan pertimbangan populis. Pemerintah harus berani menjelaskan logika ekonomi di balik angka.
Ketiga ialah proporsionalisasi porsi setoran jamaah. Setoran jamaah secara bertahap perlu dinaikkan agar mendekati biaya riil. Dengan begitu, nilai manfaat tidak terkuras, dan sistem menjadi lebih berkelanjutan.
Keempat, audit publik dan partisipasi masyarakat. Laporan BPKH dan Kementerian Haji dan Umrah harus disajikan secara sederhana dan terbuka, misalnya melalui dashboard daring yang bisa diakses jamaah. Transparansi menciptakan keadilan persepsi.
Ke depan, arah reformasi kebijakan haji harus berorientasi pada kemandirian finansial dan keadilan antar waktu. Skema subsidi besar dari nilai manfaat memang meringankan jamaah hari ini, tapi berpotensi menimbulkan beban di masa depan.
Solusinya adalah transisi bertahap menuju sistem “cost sharing berkeadilan” yaitu jamaah menanggung porsi biaya yang proporsional dengan kemampuan ekonomi, sementara nilai manfaat difokuskan untuk menjaga keberlanjutan sistem dan perbaikan layanan.
Selain itu, BPKH perlu didorong menjadi lembaga investasi syariah strategis umat, dengan portofolio yang seimbang antara likuiditas jangka pendek dan investasi jangka panjang yang produktif.
Untuk mendukung pelayanan terhadap jamaah, pemerintah saat ini tengah menyiapkan Pembangunan kampung haji. Hal ini pertama kali diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk upaya peningkatan pelayanan bagi jamaah haji asal Indonesia yang jumlahnya salah satu yang terbesar di dunia. Pembentukan kampung haji merupakan salah satu bentuk investasi langsung dalam upaya menurunkan biaya akomodasi dalam pelaksanaan ibadah haji.
Rencana itu diklaim mendapat respons positif dari Kerajaan Arab Saudi, termasuk dari Putra Mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman (MBS). Bahkan, MBS dikabarkan telah memberikan konsesi lahan seluas 50 hektare di kawasan strategis Jabal Umar selama 100 tahun kepada Indonesia. Jabal Umar berada hanya beberapa kilometer dari Masjidil Haram.
Menakar keadilan dalam penentuan biaya ibadah haji adalah upaya mencari titik temu antara spiritualitas dan rasionalitas ekonomi. Haji memang ibadah, tetapi ibadah yang diatur oleh sistem ekonomi, keuangan, dan tata kelola publik.
Keadilan bukan berarti biaya harus murah, tetapi bahwa setiap keputusan biaya mencerminkan proporsionalitas, transparansi, dan keberlanjutan. Jika nilai manfaat dikembangkan dengan investasi yang aman dan produktif, serta sistem pembiayaan haji disusun berdasarkan prinsip keadilan antar generasi, maka ibadah haji Indonesia tidak hanya sah secara syariah, tetapi juga adil secara sosial dan berkelanjutan secara ekonomi.

 3 months ago
80
3 months ago
80